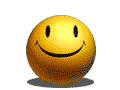Setiap
memasuki semester genap, guru yang mengajar di kelas terakhir pada
setiap jenjang satuan pendidikan, bagaikan terpenjara. Mereka dituntut
untuk membawa sukses peserta didik dalam menempuh Ujian Nasional
(UN). Demikian besar ekspektasi orang tua murid akan keberhasilan
anak-anak dalam menempuh UN, sampai-sampai sang guru lebih banyak berada
di sekolah. Berangkat pagi, pulang sore; entah memberikan les,
pemadatan materi, atau apa pun namanya. Semua dilakukan agar siswa
didiknya sukses menempuh UN dengan prestasi terbaik. Sudah bekerja
mati-matian pun belum ada jaminan bahwa anak-anak sukses menempuh UN.
Imbasnya, guru sering kali dituding sebagai pihak yang paling
bertanggung jawab terhadap kegagalan siswa dalam menempuh UN. Setelah UN
berlangsung, akhirnya siswa Lulus 100%, siapa yang dapat nama ? Gurukah
?

Dari
berbagai pengalaman selama ini, guru tak jarang mengeluh tentang
kesenjangan yang terjadi antara tuntutan kurikulum dan UN.
Pada semester
genap, misalnya, guru tidak lagi menggunakan kurikulum sebagai acuan.
Mereka lebih terfokus untuk mengajak siswanya mendalami soal-soal UN.
Bahkan, tak jarang siswa diperlakukan sebagai “bejana” yang terus
di-drill soal-soal UN, tanpa memedulikan lagi apakah materi yang
disajikan dipahami sepenuhnya oleh siswa atau tidak. Yang ada di benak
guru, semakin banyak soal di-drill-kan, siswa dianggap akan makin siap
menghadapi UN. Benarkah demikian?
Untuk
menjawab pertanyaan semacam itu bukanlah hal yang mudah. UN selama ini
telah dicitrakan sebagai penilaian terakhir yang akan menentukan lulus
atau tidaknya siswa belajar selama tiga tahun di jenjang satuan
pendidikan tertentu. Repotnya, UN juga telah dicitrakan akan membawa
nama baik, citra, dan marwah sekolah, bahkan daerah. Tak perlu heran
apabila muncul kesan bahwa UN tak semata-mata menjadi alat dan sarana
penilaian semata, tetapi juga telah merambah ke ranah birokrasi. Tak
jarang muncul tekanan dari atas ke bawah. Bupati/walikota menekan kepala
dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan menekan kepala sekolah, dan
ujung-ujungnya gurulah yang harus menanggung imbasnya. Seringkali, guru
“dipaksa” menghalalkan segala cara untuk mendongkrak nilai UN siswanya.
Tak perlu heran jika hampir setiap tahun terjadi kecurangan. Namun,
ironisnya, kecurangan demi kecurangan yang (nyaris) terjadi tiap tahun,
tak pernah diusut tuntas.
Jika
kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin generasi masa
depan negeri ini hanya akan menjadi sosok yang tidak mandiri, suka
mengambil jalan pintas, dan tidak memiliki rasa percaya diri.
Ketidakjujuran pelaksanaan UN yang mereka saksikan dengan mata kepala
sendiri makin membuktikan bahwa sikap jujur justru akan membuat
anak-anak gagal dalam meraih cita-cita. Imbas lebih lanjut, mereka juga
cenderung untuk mengambil jalan pintas, suka menipu, dan berbagai cara
tidak fair lainnya.
Sebelum
telanjur parah, ada baiknya formula UN benar-benar didesain agar
anak-anak mampu menghargai proses dan kejujuran. Dari sisi proses,
anak-anak perlu ditanamkan sikap bahwa tak ada sukses yang bisa diraih
tanpa proses kerja keras. Demikian juga dalam soal kejujuran. Sikap
seperti ini harus jelas muncul secara masif dalam pelaksanaan UN,
sehingga siswa yang tidak jujur justru akan mendapatkan hasil yang
buruk.
Jangan
sampai terjadi, UN hanya menciptakan kegelisahan di kalangan guru,
sehingga cenderung mengambil jalan pintas dan menempuh segala macam cara
untuk “menyulap” nilai siswanya jadi tinggi. UN bukanlah tujuan,
melainkan alat untuk mengukur dan memotret kemampuan siswa selama
memburu ilmu di bangku sekolah.